Bab 21
“DIA nak ikut Dhiya balik kampung,” beritahuku.
“Apa?” Mama buat muka terkejut. Padahal mama mungkin lebih tahu sebab Amar banyak berhubung dengan mama.
“Satu lagi, Puan Dina nak kenalkan Dhiya dekat anak saudara dia.”
“Ap... ap... Apa Dhiya? Dina nak kenalkan anak saudara dia? Eh, mana boleh! Sebab apa?”
Reaksi mama buat aku curiga.
“Apa salahnya. Dhiya kan solo sekarang.” Aku nak test mama. Aku dapat hidu rancangan terbaik mama dan Amar.
“Eh, kan Amar sukakan Dhiya. Kenapa nak berkenalan dengan orang lain pula? Tak payahlah. Lupakan aje pasal Dina tu. Sekarang ni, Dhiya kena fokus dengan Amar. Amar tu betul-betul sayangkan Dhiya.”
Aku mencemik. “Tak salah kan kalau Dhiya berkenalan dengan anak saudara Puan Dina tu? Lagipun, dia datang jumpa Dhiya semata-mata nak cakap pasal ni. Dhiya tak sampai hati nak tolak.”
Mama nampak gelisah. Aku tak tahu apa yang dia sudah berjanji dengan Amar. Aku yakin ini konspirasi antara mama dan Amar. Mama nak jodohkan aku dengan Amar. Ya, aku pasti yang tu. Patutlah siap ajak makan tengah hari kat rumah. “Kenapa mama nak sangat Dhiya pilih Amar?”
Mama mendengus perlahan. “Sebab Amar sayangkan Dhiya. Anak saudara Dina tu belum tentu lagi. Kita tak tahu perangai dia macam mana. Rupa dia macam mana. Entah handsome ke tidak. Tengok Amar, semua dia ada. Kacak, kaya, bergaya, ada kondo, ada banglo besar. Apa lagi Dhiya nak?”
“Dhyia tak suka sebab dia tu artis, ma. Mama tahulah macam mana artis ni. Dhiya takut Dhiya tak boleh tahan nanti. Sekarang ni pun Dhiya dengar gosip pasal dia dengan Nisha.”
“Nisha? Penyanyi baru tu?”
Aku angguk sekali.
“Be... Betul ke?” Mama seperti tak percaya saja.
“Nama pun gosip. Tak tahu betul ke tak. Tapi tu apa yang Dhiya tengok kat Internet. Tak apalah mama. Soal jodoh Dhiya, biar Dhiya pilih sendiri ya. Dhiya tak nak Dhiya yang terluka nanti. Kalau Dhiya pilih sendiri, sekurang-kurangnya Dhiya takkan salahkan sesiapa kalau Dhiya kecewa,” ujarku lalu menggenggam tangan mama.
Mama membalasnya dengan senyuman hambar. “Mama yakin Amar boleh bahagiakan Dhiya. Mama pun tak nak tengok Dhiya kecewa lagi.”
Aku senyum terharu. Bagi aku, mama bukan sekadar mama, dia juga BFF aku untuk aku ceritakan apa saja masalah. Mama sentiasa mendengar. Dia selalu menasihati dan menyokong. Asalkan aku tak buat perkara yang salah dan menjaga maruah diri.
“Dhiya, mama dah anggap Dhiya macam anak kandung mama. Mama nak yang terbaik untuk Dhiya. Mama nak Dhiya bahagia. Tapi terpulang pada Dhiya untuk pilih siapa jodoh Dhiya. Mama cuma mahukan yang terbaik dan apa-apa pun keputusan Dhiya, mama tak berhak membantah. Dhiya masih ada keluarga Dhiya untuk Dhiya rujuk.”
Perlahan aku angguk. Tubir mataku bergenang. Mama usap pipiku.
MALAM kian larut. Aku masuk ke bilik untuk berehat dan tidur. Rasa letih sangat kerana banyak berfikir.
Baru nak baring, tiba-tiba aku teringatkan buah tangan dari Istanbul yang Puan Dina berikan. Aku belum berkesempatan untuk buka lagi. Aku turun dari katil dan ke meja solek. Aku membukanya dan mengeluarkan isinya.
Aku terpegun melihat sehelai selendang bercorak yang sangat cantik. Menggabungkan warna merah hati, hitam, putih dan sedikit biru tua. Cantik sangat. Aku merasa fabriknya. Ia lembut dan mungkin diperbuat daripada sutera. Tentu mahal harganya.
Lalu aku letak di atas kepala dan lilitkan. Aku tersenyum-senyum tatkala gayakan tudung itu. Aku angkat hujung selendang letak ke atas kepala. Kemudian letak kedua-dua di bahu kiri dan kanan. Hmm, gaya apa yang sesuai ya? Nampaknya aku kena tengok tutorial lilit selendang jawabnya.
Selalunya aku cuma pakai tudung bawal. Selendang ni jarang-jarang saja. Rimas nak melilit. Pin sana dan pin sini. Apa pun, selendang pemberian Puan Dina akan menjadi selendang kesayangan aku.
AKU baru selesai berurusan dengan seorang pelanggan. Ketika itulah telefon bimbit aku di meja kaunter berbunyi lantang. Aku tunggu sehingga pelanggan keluar dan jawab panggilan. Puan Dina yang telefon.
“Helo, puan.”
“Helo, Dhiya. Ada kat kedai ke? Saya dah nak sampai ni.”
Aku tergamam. Apa? Puan Dina dalam perjalanan ke sini? Habislah... Mesti dia datang dengan Aryan Shah.
“Err... ada. Saya ada kat kedai. Datanglah.” Meskipun aku mengalukan kedatangan Puan Dina, aku tetap cemas. Dia memang serius nak kenalkan Aryan Shah untuk aku. Macam mana ni?
Aku tak sedar yang Puan Dina sudah matikan talian dia. Bila aku nak bersuara semula, taliannya senyap. Aku letak iPhone di atas meja kaunter dan mundar-mandir di situ. Apa nak buat ni? Buat air? Hari itu Puan Dina ada cakap kalau dia dan Shah datang, buatkan air. Tapi maksud aku, apa aku nak buat kalau Shah ada di sini? Mesti aku malu. Kalau mama ada, kuranglah sikit rasa malu. Mama pula keluar dan belum balik-balik.
Dalam aku dilanda cemas, iPhoneku berbunyi lagi. Daripada Puan Dina juga. Aku semakin berdebar. Dah sampai ke dia?
“Dhiya, saya minta maaf banyak-banyak. Tadi anak saya telefon. Dia accident. Lain kali ya Dhiya?”
Aku terkejut. Dalam waktu yang sama berasa lega. “Teruk ke accident?”
“Tak teruk tapi risau jugak ni. Saya nak pergi hospital dengan Aryan. Okey, Dhiya. Apa-apa nanti saya akan telefon Dhiya ya.”
“Okey.” Baru jawab okey, Puan Dina matikan talian. Cemas benar suara dia.
Aku tahu perasaan seorang ibu bila mendengar berita kemalangan terutama anak sendiri. Aku bersimpati dengan Puan Dina. Tetapi aku rasa lega sangat-sangat sebab dia tak jadi datang. Rasa macam kembali bernafas.
Baru nak duduk di meja kaunter, aku rasa lapar pula. Tengok jam, sudah 10.00 pagi. Aku belum sarapan lagi. Tanpa berlengah, aku ambil dompet dan pergi ke restoran hujung bangunan. Kedai mama aku kuncikan dulu.
Semasa berjalan ke restoran, lantas aku teringatkan pak cik yang kurang siuman itu. Dulu, semasa aku pergi beli roti canai, dia minta seringgit daripada aku. Aku rasa lepas hari itu, aku sudah tak nampak dia.
Sampai di depan restoran, aku pesan dua keping roti canai. Sambil perhatikan pak cik itu menebar roti canai, aku bertanya, “Pak cik, mana pak cik seringgit tu?”
“Dah banyak hari dia tak datang. Selalu dalam seminggu ada dua tiga kali dia datang sini minta makan. Kenapa?” soal pak cik itu kembali.
Sambil tangan giat menebar doh roti canai di atas meja yang bersih. Dicelup tangan ke dalam minyak dan uli doh itu. Aku asyik perhatikan gerak tangannya.
“Kesian dia,” kataku perlahan.
Entah di mana dia sekarang. Apa dia buat. Makan ke tidak. Tidur di mana. Mungkin ada orang menghina dan mengeji dia. Mungkin bila dia mahu makan, ada orang akan menghalau dia dengan kejam.
“Jangan risau. Nanti dia akan datang. Adalah tu dia pergi merayap ke mana-mana.” Kata-kata pak cik itu berakhir bersama roti canai yang siap dibungkus.
Aku bangun dan bayar sejumlah wang sebelum balik ke kedai. Setibanya aku di kedai, aku nampak sebuah kereta Honda yang bercermin gelap. Aku tahu siapa pemilik kereta itu. Aku abaikan dan masuk ke dalam kedai. Sebaik saja aku masuk dan letak bungkusan roti canai di atas meja kaunter, aku dikejutkan dengan kedatangan seseorang di belakang.
“Hai.”
“Hai,” balasku.
“Tak ada siapa tahu ke awak datang sini? Tak ada orang perasan?”
Dia menggeleng. “Kalau ada pun, kenapa nak takut?”
“Saya tak nak nanti keluar gosip pasal awak,” ujarku lalu duduk di meja kaunter.
Amar pergi ke ruang tamu. Aku ni tengah lapar. Amar pula datang. Macam mana aku nak baham roti canai tu?
“Gosip? Semua tu tak betul.”
“Maksud awak, datang jumpa saya kat sini tak betul? Bila wartawan tanya, awak akan nafikan dan cakap saya tak pernah pergi ke situ. Mungkin pelanduk dua serupa. Mungkin ada orang cuba nak fitnah awak. Awak nak jawab macam tu?” bidasku. Aku dapat agak sekarang. Kalau aku tanya tentang Nisha, tentu dia akan jawab sama sepertiku tadi.
“Dhiya, kenapa ni? Awak tak percayakan saya? Awak nak saya nyanyi lagi?” Amar berubah riak, namun sempat mengusik.
Bibirku mencemik. Nak nyanyi lagu Percaya Padakulah tu. Aku masih ragu dengan keikhlasannya. “Gosip awak dengan Nisha tu, macam mana?”
Amar terkejut. “Pasal Nisha?”
“Awak rapat dengan dia sekarang, kan?”
“Memanglah. Sekarang production nak saya buat lagu duet dengan dia. Mungkin sebab tu orang nampak saya rapat dengan dia.”
Oh, macam tu ke. Aku masih tak percaya. Bukan aku tahu apa dia buat di sana. Aktiviti dia selain yang ditayangkan dalam TV bukan aku tahu pun. Yang aku tahu dia selalu datang cari aku di sini.
“Dhiya, saya tahu awak susah nak percayakan saya. Tapi saya dengan Nisha cuma rakan kerja untuk lagu duet tu.”
“Kenapa awak datang sini?” soalku. Abaikan pasal Nisha.
“Nak jumpa awak. Kebetulan lalu sini,” ujarnya. “Hmm, saya ada bau roti canai dalam kedai ni.”
Aku terpandang ke arah Amar. Lalu Amar fokus ke arah kaunter.
“Awak beli roti canai?”
Berat kepala kuangguk. Nasib baik beli dua keping. Nak ajak dia sekali ke tak?
“Beli kat mana?”
“Restoran hujung sana.”
Amar pandang aku. Aku rasa dia berminat dengan bau roti canai tu.
“Awak belum makan ke?”
Amar geleng kepala. “Saya baru minum aje tadi. Rasa lapar pula. Dhiya, jom temankan saya makan kat luar.”
“Mana boleh. Saya kena jaga kedai,” bantahku.
“Sekejap aje. Takkan tak boleh.”
Aku tetap geleng. Tak boleh!
“Kalau macam tu, boleh tak kongsi roti canai tu?”
Aku terkesima. Kongsi roti canai? Kesian pula aku tengok Amar. Buatnya dia pengsan di sini lagi, aku yang susah nanti. Lalu aku bangun ke pantri sambil membawa bungkusan roti canai. Aku hidangkan sekeping roti canai ke atas pinggan dan tuang kuah ke dalam mangkuk. Ini bahagian Amar. Bahagian aku pula aku akan makan nanti.
“Makanlah,” kataku seraya meletakkan roti canai dan kuah ke atas meja. Aku ke pantri semula dan bancuh air untuknya.
Siap bancuh instant coffee, aku bawa ke luar.
“Awak dah makan?”
“Awak makanlah dulu. Saya tak nak awak pengsan kat sini lagi.”
Amar senyum meleret.
Boleh pula dia senyum. Bukan main gelabah aku dan mama waktu itu.
“Boleh saya makan?”
“Makanlah.”
Amar melafaz bismillah dan mula mencubit roti canai untuk dicicah ke dalam kuah dal. Aku perhatikan cara dia makan. Sopan walaupun nampak macam kebuluran. Sibuk sangat sampai tak sempat makan ke? Kalaulah macam ni, baik tak payah jadi artis.
Baru sekejap aku beralih pandangan, aku lihat pinggan Amar sudah licin. Terbuntang dua biji mata ni.
“Ada lagi tak?” pinta Amar.
Aku merenungnya tanpa kelip.
SELEPAS Amar kekenyangan dan aku berputih mata, Amar bersandar pada sofa. Dia memandangku yang berwajah kelat. Merenung pinggannya yang licin habis. Termasuk kuah dal. Gelas kering tanpa setitis air pun. Aku rasa sedih sebab terpaksa korbankan perut semata-mata nak tengok dia kenyang. Takpalah, dah rezeki dia. Bukan rezeki aku.
“Dhiya, kenapa monyok aje ni?”
Dia tanya kenapa aku monyok? Dia tahu tak dia telah habis-licinkan dua keping roti canai aku? Dia tahu tak yang aku belum makan apa-apa untuk pagi ni? Tapi dia bedal semua sekali sampai habis. Marahnya aku.
“Err... tak ada apa-apa.”
“Tak ada apa-apa? Awak ada masalah ke? Kalau ada, ceritalah.”
Masalah saya sekarang, awak dah habiskan roti canai bahagian saya, jeritku dalam hati.
“Tak ada apa-apa. Awak dah kenyang, kan?”
Amar angguk. Langsung tak rasa bersalah sebab cuma dia yang kekenyangan. Aku kebuluran.
“Bolehlah awak balik sekarang.”
“Kenapa? Awak tak suka saya kat sini ke?”
Terkejut dengan sangkaan Amar, aku geleng. “Bukan macam tu. Saya kena kerja.”
“Kerja? Tak ada pelanggan pun yang datang. Kerja apa yang awak maksudkan?”
Aku mendengus geram. Menjeling ke arahnya kemudian pandang ke arah lain. Dia ingat aku duduk goyang kaki saja di sini?
Sebenarnya selain sedih kerana Amar habiskan dua keping roti canai, ada perkara lain yang mengganggu fikiran aku. Patut ke aku luahkan kepada Amar?
“Saya tiba-tiba teringatkan seseorang.”
Mata Amar tiba-tiba bulat memandangku. “Siapa? Khalif?”
Ah, dia cukup pantang bila aku cakap macam tu sekarang. Pelik betul. Cemburu ke dia?
“Bukan. Ada seorang pak cik ni.”
Dia nampak lega.
Aku sambung cerita. “Hari tu saya pergi beli roti canai kat kedai hujung tu. Ada seorang pak cik ni. Kesian dia. Saya tahu dia memang tak siuman. Masa tu dia minta duit daripada saya. Mula-mula saya tak nak bagi. Lepas tu pak cik roti canai tu cakap dia tak kacau orang. Dia cuma nak duit seringgit aje. Saya bagi lima keping, dia ambil sekeping aje. Bila dapat seringgit, dia terus ketawa dan melompat-lompat. Macam nilai seringgit tu besar sangat bagi dia. Saya rasa kesian sangat kat dia. Dah lama saya tak pergi restoran hujung tu. Bila saya tanya, dia cakap pak cik tu dah banyak hari tak datang. Saya terfikir. Mana dia pergi. Dia tidur kat mana. Makan ke tak.”
“Kesian kan. Dia tak minta hidup macam tu.” Amar turut melahirkan rasa simpatinya.
“Mesti dia sebatang kara. Dia tak ada sesiapa dalam hidup dia. Dia dah tua. Saya terfikir, takkan dia nak habiskan sisa hidup dia dalam keadaan macam tu.” Aku mula diselubungi emosi.
“Kenapa tak cari dia?”
“Mana nak cari?” Aku angkat bahu. Wajah aku tundukkan. Tiba-tiba aku terpanggil untuk bantu pak cik itu.
“Saya yakin dia akan datang sini lagi. Sebab dia tahu orang kat sini baik-baik hati,” kata Amar sambil tersenyum.
Hatiku terpujuk dan dalam masa yang sama juga berharap agar dipertemukan semula dengan pak cik itu.
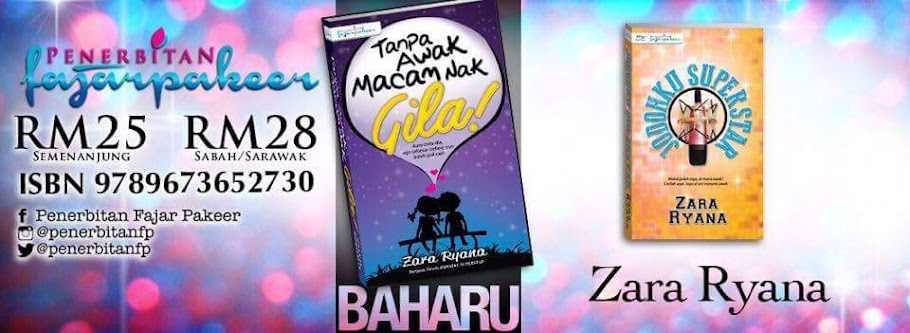

No comments:
Post a Comment